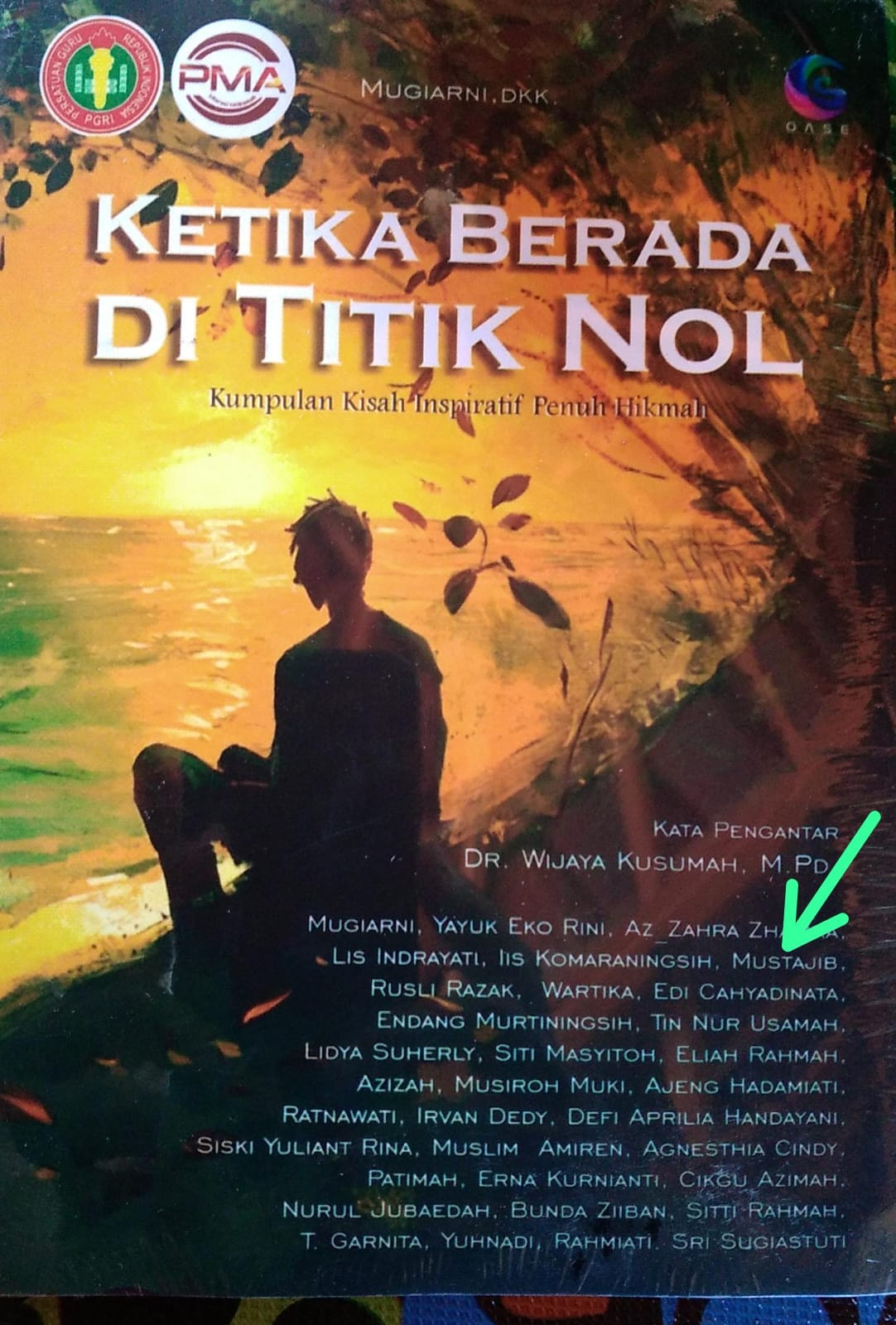Bagi penulis
pemula, yang baru coba serius dan konsisten menulis, terbitnya tulisan walau
melalui sebuah antologi merupakah sebuah barokah yang luar biasa. Dan tentunya sangat
menggembirakan! Setidaknya itulah perasaan yang saya alami dengan terbitnya
antologi Ketika Berada di Titik Nol : Kumpulan Kisah Inspiratif Penuh Hikmat
yang digagas (dieditori) oleh Bunda Kanjeng alias Bunda Sri Sugiastiastuti (www.srisugiastutipln.com) yang
telah menulis sejumlah buku ajar, novel, puisi, catatan perjalanan serta menerbitkan
belasan buku tunggal (solo) dan puluhan buku antologi.
Antologi yang
diterbitkan oleh Penerbit OASE Pustaka, Cetakan I Agustus 2024, dan di-backup sepenuhnya oleh PGRI dan
PMA itu menghadirkan 33 tulisan. Salah satu tulisan tersebut adalah hasil
goresan pena saya sendiri, dengan judul “Jangan Sombong : Sepenggal Kisah Nyata”.
Dalam tulisan ini saya coba memotret salah satu prilaku sosial yang saya anggap
sebagai sebuah cerminan kesombongan, sebuah prilaku yang sangat dibenci agama
apapun.
Untuk
menghindari kesan subyektif yang (mungkin) berlapis-lapis dari pihak pembaca
maka saya memilih untuk tidak menceritakan ulang. Melainkan, saya
mempersilahkan pembaca untuk membaca langsung sebelum mengonfirmasi apakah
benar itu suatu wujud kesombongan atau cerminan subyektifitas saya yang
berlebihan dengan menilai perbuatan tersesebut sebagai sebuah kesombongan. Berikut
tulisan lengkapnya (setelah judul “Jangan Sombong, Sepenggal Kisah Nyata”).
“Jangan pernah meremehkan
seseorang, terutama anak kecil yang sudah bisa berpikir akademis, hanya karena
alasan ekonomi dan apalagi iri hati serta sombong”
Itulah pesan yang bisa saya sampaikan berdasarkan
pengalaman nyata (wallahu) setelah di masa berstatus sebagai siswa
sekolah menengah atas (SMA) diremehkan oleh seseorang yang sudah berstatus
sebagai ibu. Rangkaian kejadiannya secara kronologis, dapat saya sampaikan
sebagai berikut.
Saya seorang anak udik, terlahir dan besar di dasan
Jempong, Bali Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dulu, dasan (dusun) Jempong
merupakan bagian dari kampung Bali Buwuh. Setelah pemekaran kampung beberapa
tahun lalu, keduanya berpisah, masing-masing berdiri secara otonom sebagai
Kampung Dasan Jempong dan Kampung Bali Buwuh. Pun demikian dengan kecamatan,
dulu Desa Darek merupakan bagian dari Kecamatan Praya Barat. Kini, Desa Darek
menjadi Ibukota Kecamatan Praya Barat Daya.
Saya terlahir dari keluarga berekonomi tandus, bahkan
boleh dikatakan minus. Sebagai gambaran, saat berstatus siswa sekolah dasar
(SD) di SDN 3 Darek, saya punya dua stel pakaian seragam. Yang beli sendiri
adalah seragam pramuka yang karena sudah lama terpakai yoke kanannya sampai
terlepas dari kancingnya. Yoke dibiarkan terus berkibar. Sementara yang satu
stel lainnya pemberian dari seorang nenek kenalan keluarga saya. Sepatu hanya
sepasang. Itu pun dibelikan saat (kalau tidak salah) kelas empat atau lima dengan
ukurang yang jauh lebih besar dari ukuran kaki (foot) dengan harapan
bisa terpakai sampai kelas enam, bahkan sampai sekolah lanjutan tingkat pertama
(SLTP, sekarang SMP).
Kegaringan
ekonomi, tidak hanya tercermin melalui kondisi di atas. Ketika masuk SMP,
dua-tiga hari setelah masuk SMP, status sebagai siswa nyaris terputus karena
tidak mampu membeli kain seragam putih-biru yang disediakan sekolah. Untung ada
yayasan yatim piatu yang mengulurkan bantuan. Berbekal surat pernyataan sebagai
seorang anak piatu dari pimpinan yayasan, saya akhirnya diperbolehkan membeli
segaram di luar sesuai kemampuan. Kain seragam yang terbeli tidak
sekualitas dengan baju yang ditawarkan di sekolah. Warnanya pun berda dengan
seragam resmi. Selain itu, selama menjadi siswa SMP, saya dibebaskan dari
pembiayaan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Saya hanyak bayar iuran
OSIS sebesar 50 rupiah, itupun kalau ada.
Alhamdulillah, Allah Sang Pengasih dan Penyayang di satu
sisi memberi ujian dengan kegersangan ekonomi. Namun di sisi lain, kemampuan
kognitif, otak atau akademis saya – menurut penilaian diri saya sendiri –
sangat “basah” alias cukup cair. Terbukti,
di catatan laporan hasil penilaian (rapor) saya, posisi saya ulang alik di ranking
1 s.d 3. Sejujurnya, masih menurut penilaian sendiri, saya bisa terus bertahan
di posisi pertama. Namun seringkali saya rasakan ada unsur-unsur primodial
(semisal status sosial kawula – darah biru) sebagai basis pelaksanaan ulangan, sehingga
saya tidak selalu di posisi teratas. Itu saya ketahui karena kenaifan atau
kepolosan sang pesaing-pesaing yang mengaku kadang-kadang diberikan bocoran
soal-soal yang akan dikeluarkan dalam ulangan. Putaran “Kisi-kisinya
(bocorannya)” terbatas.
Sewaktu di
SMP, prestasi akademis saya tidak terlalu jelek juga, walau tidak pernah
menjadi juara umum 1 dan 2, atau 3. Namun – jika tidak salah ingat -- mendekati
angka 3 pernah, terutama di kelas akhir.
Namun jika peringkat kelas dipakai sebagai ukuran, jika tidak salah
ingat, terus leading bertengger di posisi puncak, kecuali di semester 1
dan 2. Di semester 1, saya tidak ikut ulangan umum. Beberapa minggu
sebelum ulangan umum semesteran, saya terserang tipes yang hampir merenggut
nyawa. Walau tidak ikut ulangan umum, akumulasi nilai yang saya peroleh dari
tugas- tugas dan ulangan harian, saya dapat menyalip di atas 85% dari total
siswa yang ada di kelas saya. Di semester kedua, langsung mendepak pemegang
peringkat dua dan tiga, atau mungkin yang pertama. Entahlah!
Kurangnya latihan-latihan mengerjakan soal-soal
berstandar nasional, baik, secara mandiri maupun di bawah inisiatif dan
bimbingan guru-guru, dan kerasnya tekanan psikologis menghadapi Evaluasi
Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), perolehan total NEM (Nilai Ebtanas
Murni) saya tidak terlalu menggembirakan : terselip diantara angka 31 dengan
33. Dengan perolehan NEM seperti itu, saya tidak berhasil masuk di sekolah
menengah atas (SMA) Negeri yang difavoritkan oleh seantero warga masyarakat di
kabupaten kami. Saya harus puas, dan akhirnya bersyukur sekali, masuk SMAN 2
Praya yang baru dibuka pada tahun saya masuk SMA, yaitu tahun pelajaran 1985 –
1986.
Alhamdulillah, prestasi akademis di SMAN 2 Praya cukup
moncer. Selama dua semester di kelas 1, nasib menempatkan saya di peringkat
ke-4 di kelas. Sepertinya, begitu. Di semester pertama kelas 2, peringkat saya
terkoreksi menjadi peringkat ke-2 walaupun total raihan nilai sama dengan
penikmat peringkat pertama. Saya ditempatkan di urutan kedua, dari sas-sus yang
beredar, antara lain karena saya berstatus sebagai pendatang baru di kelas
pilihan akhir. Ya, saya memang pindah kelas dari kelas fisika (A1) ke kelas Program
Budaya dan Bahasa (A4) dua atau satu minggu menjelang ulangan semester pertama.
Di kelas pilihan tersebut saya bisa mengembangkan bakat
dan minat seperti di bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sastra
Indonesia, sastra Melayu dan ilmu-ilmu sosial semisal sosiologi dan geografi,
termasuk sejarah. Kelas pilihan ini mengantar saya menempati peringkat pertama
di kelas sejak semester 2 kelas 2 hingga tamat. Bahkan saya menjadi peraih NEM
tertinggi di sekolah saya. Alhamdulillahnya lagi, saya diterima masuk perguruan
tinggi tanpa tes, yakni melalui jalur seleksi PMDK (Penelusuran Minat Dan
Kemampuan). Perguruan tingginya di luar daerah NTB. Jurusannya, untuk ukuran di
desa saya, cukup mentereng : Bahasa Inggris. Jadilah saya menjadi orang pertama
di kampung saya kuliah jurusan bahasa Inggris di luar daerah, tepatnya di Universitas
Udayana, Bali.
Kata orang,
masa-masa di SMA adalah masa-masa yang penuh kenangan, dalam suka maupun duka.
Saya pun merasakan hal seperti itu. Rasa “suka” itu dikarekan capaian-capaian
akademis sebagaimana saya paparkan di atas. Sementara rasa ‘duka” tercipta
karena secara ekonomis dan sosial diremenkan oleh seorang ibu yang orangtuanya
tak lain adalah tetangga saya di kampung. Ringkasan ceritanya sebagai berikut.
Sewaktu mau
naik ke kelas 3 SMA, sekolah mengundang orangtua atau wali murid untuk
mengambil rapor anaknya masing-masing. Karena keterbatasan ekonomi, wawasan dan
kesempatan, bapak saya tidak bisa datang untuk mengambil rapor. Ibu jelas tidak
bisa datang karena beliau telah meninggalkan saya menghadap Illahi Robbi
sewaktu saya masih sangat belia sehingga wajahnya tidak dapat saya simpan dalam
memori saya. Lalu, apakah “perempuan” yang meremehkan itu yang datang mewakili
orangtua saya untuk menganmbil rapor kenaikan kelas saya? Tidak!
Yang datang
adalah adiknya, sama-sama perempuan, senior satu tingkat semasa di SMP. Senior
ini sesungguhnya siswi salah satu SMA Swasta di kota Mataram, Ibukota Provinsi
NTB. Pada hari pembagian rapor itu, entah untuk keperluan apa, mungkin sehabis
menerima rapor kenaikan kelas juga di Mataram, sang senior itu ke sekolah saya,
masih mengenakan seragam putih abu. Oh, ya, saya baru ingat, sang senior datang
ke SMA saya untuk mengambilkan rapor adiknya yang satu tingkat di bawah saya,
di SMA yang sama. Melihat sang senior yang mungkin sudah selesai mengambilkan
rapor adiknya, dan karena tidak ada pilihan lain agar rapor bisa saya bawa
pulang kampung, akhirnya saya meminta bantuan sang senior untuk menemui wali
kelas saya, Pak Kamali, untuk mengambil rapor. Alhamdulillah, diperbolehkan.
Ketika sudah
keluar dari ruang kelas tempat pembagian rapor, sambil menyodorkan rapor dan
tersenyum, sang senior (kurang lebih) berkata, “Selamat, ya. Hebat!”. Saya pun
dapat menduga-duga penyebabnya. Yakni, bahwa nilai semester 2 saya berhasil
mendepak peringkat pertama di semester 1 yang lalu. Dan ternyata, benar!
Sepertinya
berita kesuksesan itulahlah yang diceritakan atau dibisikkan oleh sang senior
kepada kakaknya saat secara kebetulan melintas dekat rumahnya. Perempuan itu, kakanya
itu, dengan suara yang cukup jelas membentur genderang kedua telinga saya,
berkata (dalam bahasa Sasak, kurang lebih), “Timakn sak hebat, timakn sak
penter, care nane, mum edak kepeng jek demak jeri ape-ape.” Terjemahan
bebas dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini, “Walaupun hebat, walaupun
pintar, di zaman seperti sekarang ini, kalau tidak punya uang, tidak akan jadi apa-apa”.
Dari nadanya dan segala konteks sosial-ekonomis yang melingkupi saat itu, frase
“tidak (akan) jadi apa-apa” itu lebih merujuk pada “menjadi pegawai negeri”
alias PNS (Pegawai Negeri Sipil). Saya bisa memastikan bahwa berkata seperti
itu merupakan sesuatu yang disengaja karena saya sedang melintas dekat rumahnya.
Dan saya lihat, perempuan itu melirik ke arah saya juga.
Saat itu, menengar kata-kata seperti itu, saya tidak
bisa berbuat apa-apa selain mencoba menelan kata-katanya. Semua serba fakta.
Bahwa saya dikatakan ‘hebat’, itu kata-kata adiknya. Saya dianggap ‘pintar’,
ya, mungkin karena data-data di rapot SMA saya, yang dilihat sang senior. Dan
bahwa kami orang tak berpunya secara ekonomis, sudah bukan menjadi rahasia
umum, paling tidak, bagi orang-orang di kampung saya dan sekitarnya. Apakah
kata-kata itu menjadi bara dendam, pembakar amarah, atau pemicu semangat,
entahlah! Saya tidak tidak tahu, saya tidak bisa memastika secara mutlak.
Yang pasti, waktu berlalu. Dengan status sebagai lulusan
pamucak pada jurusan bahasa inggris angkatan terakhir Diploma 3 FKIP
Universitas Udayana, saya mendapatkan ‘reward (hadiah)’ untuk diangkat
sebagai guru negeri (PNS) tahun berikutnya dan ditempatkan di sekitar kampus
supaya bisa melanjutkan ke jenjang program Sarjana Strata 1 (S1).
Alhamdulillah, tahun 1992, Surat Keputusan (SK) CPNS pengangkatan saya sebagai
guru SMA keluar, diperbantukan di SMA PGRI 2 Buleleng, Singaraja, Bali. Tahun
1996, studi S1 saya kelar. Tahun 2002, bersama keluarga, saya bisa pulang
kampung dan bertugas di SMAN 3 Mataram. Tahun 2015, saya diangkat sebagai
kepala sekolah (Kepsek) di SMPN 17 Mataram, lalu tahun berikutnya dipromosi ke
SMPN 12 Mataram.
Selanjutnya, tahun 2021, karena nasib dan takdir Allah
azza wajalla – bukan parena pintar apalagi mumpuni, saya dinyatakan lulus
seleksi sebagai Kepsek untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dengan
rencana awal penempatan di Sekolah Indonesia Makkah (SIM), lalu dialihkan ke
Sekolah Indonesia Riyadh (SIR). Walaupun tidak jadi tinggal di Makkah,
alhamdulillah, kadarullah, saya berserta keluarga bisa berkali-kali ke Makkah,
baik untuk keperluan berhaji bersama istri dan mengumrahkan keempat orang anak kami,
lebih dari sekali. Bahkan cuti
tahunan pada 2022 dan 2023 pun dilewati di Kota Suci umat Islam itu.
Insha Allah,
perempuan yang meremehkan saya tahu semua capaian-capaian di atas. Saya berani
memastikan itu. Yang tidak berani saya pastikan adalah apakah perempuan itu
masih ingat kata-katanya yang meremehkan orang lain itu. Saya juga tidak bisa
memastikan apa yang akan dikatakan dan/atau seperti apa gelagatnya jika kami
bertemu setelah saya sudah pulang kampung nanti. Apakah ia akan diam seribu
basa, menundukkan wajah untuk menyembunyikan rasa malunya, atau kepalanya akan
tetap tegak (terkesan ‘pongah’ atau sombong) seperti ketika mengeluarkan
kata-kata yang merendahkan dulu itu? Entahlah! Jika saya dan dia masih sama-sama
sehat dan diberi umur panjang, insha Allah sampai akhir 2024 ini, insya Allah
kami pasti bersua.
Maafkan, saya
terpaksa mengungkapkan semua ini. Tujuannya bukan untuk memuntahkan rasa dendam-amarah-kesumat
atau menjelek-jelekkan. Melainkan, melalui tulisan ini – dan semoga sempat dibaca
yang bersangkutan -- saya mengingatkan dan menyadarkan perempuan itu -- dan orang-orang
seperti dia -- agar tidak tidak meremehkan orang lain lagi, terutama
anak-anak yang sudah berakal dan masih punya potensi menggunung berkali-kali
besarnya Gunung Renjani (di Lombok) untuk berkembang dan menuai sukses dunia
dan akhirat. Meremehkan adalah wujud kesombongan yang sangat dimurkai Allah
Sang Penguasa Alam Dunia – Akhirat.
Sekali lagi,
maafkan saya, ya, Kak Tuan*. Jangan sombong lagi, nggeh?! PeaceI!!
Catatan :
· *Panggilan hormat untuk
senior yang sudah berhaji di Lombok
Riyadh, 14 Maret 2024
Dilpomatic Quarter (DQ), Riyadh, Arab Saudi